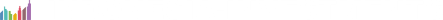Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter
Suharto (1921-2008), Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Soekarno, telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pihak lain yang bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara, yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada tahun 1950an waktu perlu menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia.
Keempat kelompok ini sangat saling mencurigai satu sama lainnya. Ketidakpercayaan ini kemudian memuncak pada tragedi di pertengahan 1960an ketika sekelompok perwira aliran kiri, karena pengaruh Partai Komunis Indonesia (menurut versi tentara), melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh tujuh pimpinan utama militer yang mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Suharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan ini, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang segala kekacauan ini. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatra, Jawa and Bali. Walaupun banyak fakta tetap tidak diketahui kebenarannya, jelas bahwa Jenderal Suharto muncul sebagai pemilik kekuasaan yang besar di tengah kekacauan di tahun 1960an.
Peralihan Kekuasaan: Orde Lama menjadi Orde Baru
Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Suharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Suharto. Suharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia.
Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang sehingga Suharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut 'Orde Baru' dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah Suharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia Barat, yang telah dihancurkan Soekarno, dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan.
Langkah selanjutnya yang dilakukan Suharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya (Presiden). Golkar (akronim dari Golongan Karya, atau kelompok-kelompok fungsional) digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Suharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti persatuan-persatuan buruh, petani dan pengusaha) yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik.

Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan Pemerintah Pusat. Para pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung Golkar sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan kemenangan besar untuk Golkar pada pemilihan umum 1971.
Untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Suharto 'mendorong' sembilan partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal dua partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum.
Pemerintahan yang Semakin Otoriter
Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan (penjelasan lebih mendetail ada di bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijkan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa (yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian).
Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut 'Kerusuhan Malari'. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak bisa menguasai massa. Kuatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru (yang lebih menekan) dilaksanakan oleh Pemerintah. Dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik (seperti demonstrasi) segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini - dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia - adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi.
Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timor Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal - dan deklarasi kemerdekaan Timor Timur pada 1975 - militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini; sebuah invasi yang diiringi kekerasan.

Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila (lima prinsip pendirian Negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Suharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tidakan-tindakan anti-Pancasila.
Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980an, Suharto berada di puncak kekuasaanya. Setiap pemilu dimenang secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Suharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting yaitu kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda Indonesia. Karena arena politik adalah area tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah didiskusikan di mesjid-mesjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi (yang akan segera dihentikan juga bila terjadi). Kebangkitan Islam itu menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990an.
Perubahan Fokus ke Islam
Karena kekuatan-kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum Muslim dari organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik (kebijakan) Suharto. Suharto (seorang muslim tradisionalis yang tidak terlalu religius) mulai melakukan pendekatan baru pada Islam pada awal 1990an. Ini termasuk jiarah naik haji Suharto ke Mekkah pada tahun 1991, penempatan para perwira yang lebih 'ramah Islam' di pucuk pimpinan militer, dan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI didirikan lebih sebagai sebuah tempat menyuarakan masukan-masukan dari umat Muslim untuk kebijakan publik daripada sebuah organisasi politik berbasis massa. Keanggotaannya mencakup para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan juga menteri-menteri kabinet. Semua upaya yang dikombinasikan ini memang berhasil untuk sedikit mengurangi kritikan dari komunitas Muslim.
Oposisi yang Semakin Menguat
Selama era 1990an, Pemerintah Orde Baru Suharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin asertif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesuksesannya sendiri: perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan dan mereka yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apa pun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan-kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Suharto (kroni-kroninya). Dari tahun 1993, demonstrasi-demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan, misalnya sebuah lotere yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh para mahasiswa maupun kelompok-kelompok Muslim. Terlebih lagi, beberapa pejabat yang didukung pemerintah pusat dikalahkan saat pemilihan umum di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa rejim Suharto bukannya tanpa kelemahan.
Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarnoputri (puteri dari Soekarno) dipilih sebagai ketua umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rejim Suharto, dilihat sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah pusat mendukung Suryadi di sebuah konggres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum namun Megawati jelas menolak mengakui hasil dari konggres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI dan juga bentrokan-bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Suharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan puteri Sukarno.

Hancurnya Orde Baru Suharto
Legitimasi pemerintahan otoriter Suharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusasaan di tahun 1960an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh (seperti Bank Dunia) menyatakan Indonesia sebagai 'Keajaiban Asia Timur' pada tahun 1990an. Istilah-istilah lain yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai 'Macan Asia' dan 'High Performing Asian Economy' (HPAE). Tentu saja, komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah. Namun, ironisnya, karakteristik Orde Baru yang supresif juga menjadi kuncinya dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan tahun 1960an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Indikator-indikator sosial lain (seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup) menunjukkan hasil-hasil positif yang serupa.
Gaya pemerintahan Suharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya. Selama dekade terakhir pemerintahan Suharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Suharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, Pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini.
Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika Krisis Finansial Asia melanda pada tahun 1997-1998 (penjelasan lebih mendetail ada di bagian Krisis Finansial Asia). Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru (tanpa kehadiran Suharto). Jakarta berubah menjadi medan pertempuran tempat kerusuhan-kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari seribu orang dibunuh. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sekutu dekat Suharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era Reformasi.
Klik di sini untuk membaca mengenai era Reformasi Indonesia